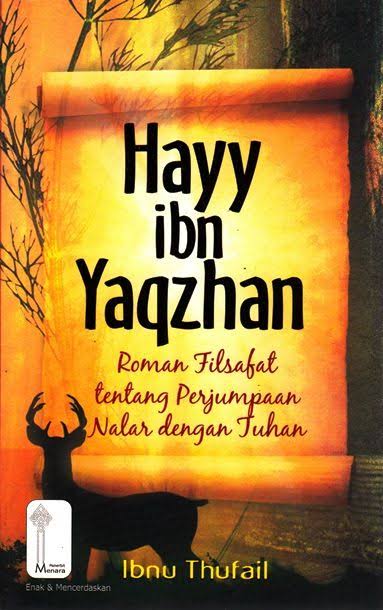Novel karya Ibnu Thufail, Hayy bin Yaqzan, tidak hanya menampilkan karakter Hayy bin Yaqzan. Seorang yang hidup terasing di sebuah pulau terpencil. Lewat proses pengamatan (inderawi) dan perenungan (akal) mampu mencapai derajat kasyf. Selain Hayy bin Yaqdzan terdapat tokoh lain bernama Absal. Seorang yang pernah mendapat seruan dakwah dari salah seorang Nabi yang menuntunnya pada derajat kasyf.
Ibnu Thufail telah menampilkan dua model cara pandang dalam memahami hakekat kehidupan lewat dua karakter yang berbeda secara ontologis dan epistemologis. Sosok Hayy bin Yaqzan merupakan seorang yang memiliki karakter positivistik. Pengetahuannya diperoleh lewat pengalaman empiris dan rasionalitas. Tokoh ini mengontruksi pengetahuannya berdasarkan pengalaman empiris secara terus-menerus sampai ia mencapai derajat pengetahuan kasyf.
Sedangkan tokoh Absal mewakili karakter bangsa Timur yang religius setelah mendapat seruan dakwah dari seorang Nabi. Ia memperoleh ilmu pengetahuan berdasarkan sumber wahyu yang dipahami secara normatif. Dengan pengetahuan normatif ia berhasil mencapai derajat kasyf.
***
Derajat kasyf dalam novel Ibnu Thufail bersumber dari pengalaman empiris dan wahyu sekaligus. Konsep kasyf itu sendiri sebenarnya sepadan dengan konsep ma’rifat menurut Ibnu Taimiyyah. Konsep ma’rifat dalam pandangan Ibnu Taimiyyah dipahami sebagai ilmu manifestasi dari nama-nama ketuhanan (madzhar al-kalimaat al-ilahiyyah) yang diisyaratkan dalam al-Quran (Majid ‘Arsan Al-Kailaniy, 1986: 118). Konsep ma’rifat menurut Ibnu Taimiyyah hanya bersumber dari wahyu, sedangkan Ibnu Thufail meyakini derajat kasyf dapat dicapai lewat pengalama empiris.
Dengan demikian, menurut Ibnu Thufail, kasyf menjadi tujuan dalam proses belajar. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyyah, ma’rifat merupakan bagian dari pendidikan tauhid. Dengan kata lain, ma’rifat dalam pandangan Ibnu Taimiyyah adalah pendidikan tauhid yang bertujuan untuk mengenal Allah SWT (ma’rifatullah).
Sesungguhnya, para filosof muslim terdahulu sudah mengenalkan konsep ma’rifat sebagai suatu bentuk kecerdasan yang berdimensi ganda: duniawi dan ukhrawi. Dalam konteks pendidikan, kecerdasan ma’rifat menurut Ibnu Thufail cukup progresif ketika ia menganggap pengalaman empiris mampu mengantarkan seseorang menuju derajat kasyf. Derajat pengetahuan tertinggi ini pun dapat dicapai lewat ajaran wahyu. Dengan demikian, Ibnu Thufail telah menawarkan dua corak epistemologi dalam pendidikan Islam.
Berbeda dengan Ibnu Thufail, konsep Ibnu Taimiyyah tentang ma’rifat hanya bersumber pada satu jenis sumber ilmu pengetahuan, yaitu wahyu (al-Quran). Walaupun hanya menggunakan sumber epistemologi yang tunggal (wahyu), tetapi Ibnu Taimiyyah mampu mensinergikan kategori ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu non agama.
***
Justru, menurut Ibnu Taimiyyah, ilmu-ilmu non agama menjadi pendukung dalam proses implementasi ilmu-ilmu agama dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, pada tataran akiologis, Ibnu Taimiyyah sudah memberikan ruang bagi proses integrasi keilmuan dalam Islam yang selama ini seakan-akan berpisah dengan ilmu-ilmu umum (sekuler).
Konsep kecerdasan ma’rifat tampaknya bisa menjadi alternatif ketika peradaban Barat yang berbasis pada ilmu pengetahuan positivistik telah menyisakan cacat bawaan. Menurut Abdul Munir Mulkhan (2004), cacat bawaan modernitas telah menciptakan ketidakadilan, konflik, dan kemiskinan global. Saat ini, nilai etik dan moral telah dimaterialisasi sehingga mengakibatkan ketimpangan sosial. Perang antar bangsa, kerusakan lingkungan, dan penyebaran penyakit mematikan telah mengancam eksistensi manusia.
Editor: Yahya FR